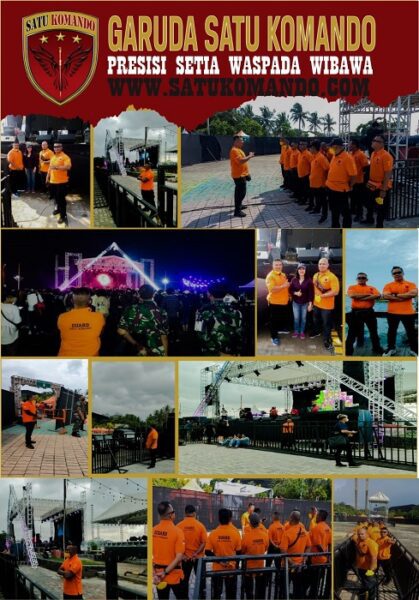Opini |
Selama lebih dari tiga abad penjajahan kolonial, para pahlawan Nusantara melakukan perlawanan bersenjata dengan gagah berani. Dari Aceh tercatat Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien, hingga di Maluku ada Pattimura dan Maria Tiahahu. Ribuan syuhada gugur dalam perjuangan tersebut. Namun, semangat mereka kerap terhalang oleh politik pecah-belah (divide et impera) yang dijalankan penjajah.
Sebagai contoh, makam-makam serdadu Belanda di Aceh banyak mencatat nama-nama prajurit dari Jawa dan daerah lain di Nusantara. Demikian pula Perang Diponegoro (De Java Oorlog) menelan korban 14.000 lasykar Diponegoro - sebagian besar orang Jawa - serta 8.000 serdadu Belanda, yang terdiri atas sekitar 1.000 orang Eropa dan 7.000 prajurit dari berbagai daerah Nusantara. Fakta ini menunjukkan betapa politik adu domba kolonial berhasil melemahkan semangat kemerdekaan para pejuang.
Dengan menelusuri kembali alur perjuangan bangsa, kita menemukan bahwa perlawanan terhadap dominasi asing - baik terhadap kekuasaan Mongol maupun penjajahan kolonial Belanda - akan lebih berhasil jika didasari pengejawantahan jiwa budaya dalam semangat berbangsa dan bernegara.
Pengalaman sejarah membuktikan bahwa kekuatan budaya tidak hanya mampu mengusir penjajah, tetapi juga mengantarkan kita menuju Proklamasi 17 Agustus 1945.
Belanda, dengan wilayah negara dan penduduk hanya sebesar Priangan, sejatinya tidak akan mampu menguasai Nusantara tanpa strategi divide et impera.
Keagungan Budaya Era Majapahit
Majapahit berhasil mewujudkan wawasan Nusantara yang luas, terbentang dari Madagaskar hingga Pulau Paskah, di bawah pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk (1350–1389). Kejayaan ini didukung oleh para budayawan dan pujangga yang visioner, antara lain Mpu Tantular yang menulis Kitab Sutasoma pada abad ke-14. Karya tersebut mengisahkan perjalanan Pangeran Sutasoma yang berhasil mempersatukan bangsanya - yang menganut Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lokal - untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Dari kitab ini lahir semboyan Bhineka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa, yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua.”
Pada periode yang sama, Mpu Prapanca menulis Kakawin Negarakertagama, yang menggambarkan keagungan Majapahit serta tata pemerintahan yang tertib dan damai dalam menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga. Makna Negarakertagama dapat ditafsirkan sebagai “iman agama yang suci dalam bernegara,” suatu konsep yang menekankan keterhubungan antara spiritualitas, pemerintahan, dan kehidupan rakyat. Nilai inilah yang memperkokoh jiwa budaya berbangsa dan bernegara di era Majapahit.
Kedua karya pujangga ini bukan hanya menjadi saksi kejayaan Majapahit, melainkan juga “pupuk budaya” yang menopang pemerintahan serta mengilhami para prajuritnya dalam menaklukkan samudra. Armada Majapahit pada masa Hayam Wuruk terbukti sangat perkasa, bahkan mampu menghancurkan armada Mongol yang dipimpin Laksamana Khubilai Khan - penguasa yang sebelumnya menaklukkan sejumlah kerajaan di Eropa.
Pengayaan Budaya Jawa dengan Iman Agama Islam
Raden Patah, yang memiliki nama kecil Jin Bun, adalah putra dari selir Brawijaya V dan menantu Sunan Ampel, salah seorang Wali Sanga. Latar belakangnya yang berakar dari daratan Cina serta ajaran Islam menjadikannya figur penting dalam peralihan budaya di Jawa. Sebagai Sultan Syah Alam Akbar (1475–1518), pendiri Kesultanan Demak, ia dikenal sangat dekat dengan nilai-nilai Islam yang disebarkan para wali.
Dengan pendekatan konvergen, para wali dan Raden Patah memperkaya budaya Jawa melalui iman Islam, dengan semboyan yang populer: “Arab digarap, Jawa digawa.” Melalui proses ini, praktik-praktik animisme yang masih kuat dihapuskan, sementara adat istiadat Jawa diperkaya dan disinergikan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi perayaan Idul Fitri, misalnya, berkembang menjadi peristiwa budaya besar di Jawa yang hingga kini memiliki ciri khas tersendiri, bahkan tidak ditemukan di belahan dunia Islam lainnya.
Selain itu, kesenian Jawa seperti lakon pewayangan juga mendapat dukungan dari Raden Patah, sehingga menjadi sarana dakwah dan penguatan budaya. Penguatan konsentrisitas budaya ini menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat Nusantara bahwa mereka mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
Kekuatan budaya tersebut juga tercermin dalam bidang militer. Raden Patah mengutus Pangeran Pati Unus, yang dijuluki Sabrang Lor, untuk memimpin armada laut Demak. Dengan perahu-perahu jung Jawa, armada ini berhasil menandingi bahkan menghancurkan kekuatan Portugis di Malaka, salah satu pusat perdagangan penting di Asia Tenggara saat itu.
Sultan Agung Melawan VOC dengan Senjata dan Jiwa Budaya
Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613–1645) dikenal sebagai raja multitahenta. Ia adalah seorang budayawan, pemimpin militer, sekaligus negarawan yang piawai dalam politik, ekonomi, dan sosial. Sebagai budayawan, ia menciptakan Kalender Saka-Komariyah yang lengkap dengan perhitungan windu, wuku, pasaran, neptu, dan mangsa. Kalender ini hingga kini masih dijadikan pedoman orang Jawa dalam berbagai aktivitas, mulai dari perdagangan (dagang), pertanian, hingga pelayaran (layar).
Filosofi budaya Sultan Agung tercermin dalam Serat Sastra Gending, yang menekankan hubungan erat antara seni, rasa, dan spiritualitas. Salah satu petikan ajarannya berbunyi:
Dene ingran tembang gending yaiku tuk ireng swara linuhung, amiji asmaning dhat, swara saking osik wadi, osik mulya wasitaning cipta surasa.
Artinya, tembang gending adalah sumber suara luhur, memuji Nama Dzat Yang Maha Suci, suara hati yang berasal dari rahasia semesta, serta gerak jiwa luhur yang menjadi penuntun kemuliaan cipta dan rasa.
Sultan Agung mewajibkan seluruh rakyat Mataram untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan filsafat budaya Jawa secara luas, terutama melalui kesenian sebagai bentuk pengejawantahan budaya.
[Bersambung]